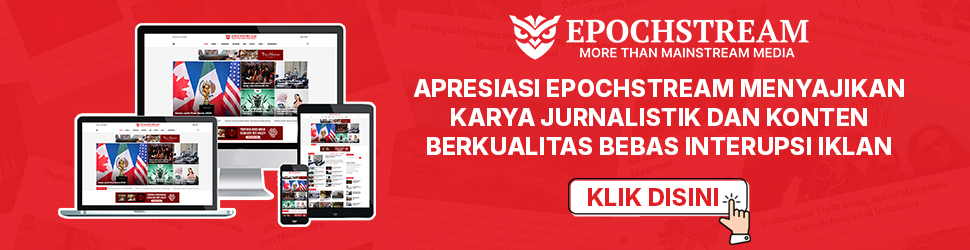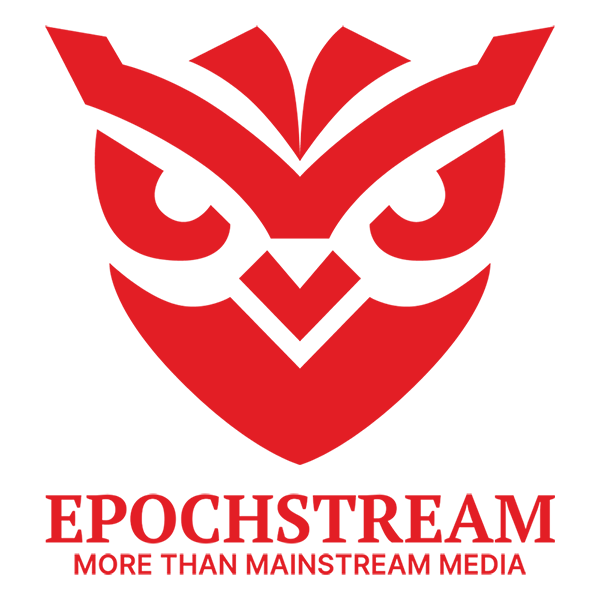Praktik tantiem komisaris BUMN yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahun kembali menjadi sorotan. Meski frekuensi rapat dan kontribusi terhadap keputusan strategis relatif rendah, remunerasi tetap tinggi. Fenomena ini menimbulkan risiko moral hazard dan potensi konflik kepentingan, karena banyak komisaris ditunjuk berdasarkan kedekatan politik, bukan kapabilitas profesional.
Ruben Cornelius Siagian, analis kebijakan publik independen dan pengamat politik, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang struktur komisaris BUMN sebagai reformasi strategis. “Ini bukan sekadar soal pengurangan tantiem. Reformasi ini menekankan profesionalisme, meritokrasi, dan akuntabilitas,” ujar Ruben.
Reformasi komisaris BUMN yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara yang selama ini kerap menghadapi kritik terkait profesionalisme dan akuntabilitas. Kebijakan ini melibatkan sejumlah aktor kunci yang memiliki kepentingan berbeda, mulai dari pemerintah sebagai pengambil keputusan utama, komisaris dan direksi BUMN sebagai penerima tantiem, hingga publik dan investor yang menjadi pihak terdampak langsung dari kinerja dan transparansi BUMN.
Praktik tantiem tinggi sebenarnya bukan fenomena baru dalam BUMN, melainkan telah menjadi bagian dari kultur remunerasi yang selama ini jarang dikaitkan secara jelas dengan pencapaian kinerja. Peningkatan perhatian publik terhadap kebijakan terbaru muncul setelah Presiden Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab finansial. Reformasi ini diterapkan lintas sektor strategis seperti energi, transportasi, infrastruktur, dan perbankan, yang memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian nasional. Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan prinsip Corporate Governance yang menekankan keterkaitan antara kompensasi, kinerja, dan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders).
Kebutuhan reformasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris. Selama ini, remunerasi komisaris sering tidak sebanding dengan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Penempatan komisaris berdasarkan pertimbangan politik, bukan kompetensi teknis, terbukti meningkatkan risiko manajerial dan menurunkan efisiensi operasional. Ruben menegaskan bahwa tujuan jangka panjang dari reformasi adalah menanamkan budaya meritokrasi, memperkuat transparansi internal, dan membangun reputasi BUMN yang sehat di mata publik dan investor. sehingga reformasi bukan sekadar pengaturan finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memperkuat institusi.
Dalam praktik implementasi, pemerintah menetapkan sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah penghapusan tantiem bagi komisaris atau direksi yang mencatat kerugian, pembatasan jumlah komisaris antara empat hingga enam orang, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara objektif dengan pengawasan independen. Aspek pengawasan independen ini krusial, karena keberhasilan reformasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan meminimalkan intervensi politik. Tanpa pengawasan yang kredibel, setiap kebijakan berpotensi menjadi retorika semata, tanpa berdampak nyata pada profesionalisme BUMN.
Jika dilaksanakan dengan konsisten, reformasi ini dapat memicu perubahan signifikan dalam budaya organisasi, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan membangun kepercayaan publik serta investor. Ruben menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar soal pengaturan gaji dan tantiem, melainkan ujian nyata komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang melayani kepentingan rakyat, bukan alat politik semata. Dari perspektif teori manajemen strategis, langkah ini sangat penting untuk memperbaiki reputasi institusi dan menarik investasi yang berkelanjutan.
Reformasi komisaris BUMN yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara, namun langkah ini tidak bebas dari risiko. Berdasarkan teori manajemen strategis dan Corporate Governance, setiap perubahan struktural dalam organisasi yang memiliki budaya remunerasi kuat berpotensi menimbulkan resistensi internal.
Komisaris dan direksi yang kehilangan tantiem atau posisi strategis mungkin menunjukkan penolakan pasif maupun aktif, mengingat banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan kompensasi yang signifikan tanpa mekanisme insentif yang jelas dapat menurunkan motivasi dan loyalitas manajerial. Oleh karena itu, reformasi harus disertai sosialisasi yang transparan dan sistem insentif berbasis kinerja untuk menjaga komitmen internal.
Meski reformasi menetapkan pembatasan jumlah komisaris dan evaluasi kinerja yang objektif, risiko politisasi penunjukan kembali tetap ada. Literatur Corporate Governance menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengangkatan pejabat strategis, karena penempatan berbasis politik cenderung meningkatkan risiko manajerial dan menurunkan efisiensi operasional. Solusi yang direkomendasikan adalah pembentukan komite seleksi independen, yang melibatkan akademisi dan pengawas eksternal, sehingga prinsip kompetensi dan integritas tetap terjaga.
Evaluasi kinerja juga menjadi titik kritis reformasi. Tanpa indikator yang terukur dan standar nasional atau internasional, proses ini bisa menjadi formalitas belaka. Penelitian empiris menunjukkan bahwa audit independen secara rutin dapat meminimalkan bias dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga pemerintah perlu memastikan evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan.
Risiko lain yang tidak kalah penting adalah potensi intervensi politik dalam pengawasan independen, yang bisa melemahkan kredibilitas kontrol internal. Pengalaman di sejumlah BUMN sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa mandat hukum yang jelas dan mekanisme rotasi pengawas, pengawasan seringkali kehilangan efektivitas. Karenanya, perlu ditetapkan regulasi yang memperkuat posisi pengawas independen, termasuk kewajiban transparansi laporan kinerja.
Dari perspektif psikologi organisasi, perubahan mendadak pada struktur remunerasi juga dapat menimbulkan efek jangka pendek terhadap motivasi komisaris dan direksi. Banyak penelitian menyebutkan bahwa bonus berbasis pencapaian target yang jelas dapat menjadi alat mitigasi efektif, menjaga produktivitas meski struktur gaji berubah.
Selain itu, publik dan investor cenderung skeptis terhadap konsistensi reformasi, terutama jika implementasi tidak terlihat nyata. Teori legitimasi organisasi menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi publik yang konsisten adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Pemerintah perlu mempublikasikan laporan berkala, menampilkan capaian dan langkah korektif, agar reformasi tidak hanya menjadi janji retoris, tetapi terlihat sebagai perubahan nyata.
Adapun risiko birokrasi lambat dalam pelaksanaan reformasi lintas sektor strategis tidak bisa diabaikan. Pengalaman di sektor energi, transportasi, dan perbankan menunjukkan bahwa tanpa roadmap implementasi bertahap dengan timeline dan evaluasi berkala, reformasi mudah terhenti di tengah jalan. Penetapan rencana implementasi yang sistematis dan terukur akan menjadi penentu keberhasilan jangka panjang.
“Reformasi komisaris BUMN bukan sekadar soal pengaturan tantiem atau struktur organisasi, tetapi ujian nyata komitmen pemerintah untuk menegakkan keberpihakan kepada rakyat. Di momen semangat 17 Agustus ini, reformasi harus menjadi cerminan tekad bangsa untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga BUMN benar-benar menjadi instrumen ekonomi yang melayani kepentingan publik, bukan alat politik semata,” ujar Ruben Cornelius Siagian.
Referensi
- Aggerholm, Helle Kryger, and Christa Thomsen. “Strategic Communication in Contexts of High Sustainability Pressure: Balancing Purposefulness, Transparency and Participation in Pursuit of Organizational Legitimacy.” Journal of Communication Management 28, no. 1 (2024): 58–73.
- Armanu, Armanu, and Sudjatno Sudjatno. “The Effect of Direct and Indirect Compensation to Motivation and Loyalty of the Employee.” Jurnal Aplikasi Manajemen 15, no. 1 (2017): 25–32.
- Cuevas-Rodriguez, Gloria, Jaime Guerrero-Villegas, and Ramón Valle-Cabrera. “Corporate Governance Changes, Firm Strategy and Compensation Mechanisms in a Privatization Context.” Journal of Organizational Change Management 29, no. 2 (2016): 199–221.
- Filatotchev, Igor, and Chizu Nakajima. “Corporate Governance, Responsible Managerial Behavior, and Corporate Social Responsibility: Organizational Efficiency versus Organizational Legitimacy?” Academy of Management Perspectives 28, no. 3 (2014): 289–306.
- Mrabure, Kingsley O, and Alfred Abhulimhen-Iyoha. “Corporate Governance and Protection of Stakeholders Rights and Interests.” Beijing l. Rev. 11 (2020): 292.
- Pangestu, Amadea Paulina, Selly Agustia, and Rathria Arrina Rachman. “Pengaruh Pemberian Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia.” Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 2, no. 1 (2019): 49–77.
- Sari, Ratna, and Muslim Muslim. “Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review.” Amkop Management Accounting Review (AMAR) 3, no. 2 (2023): 90–106.